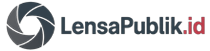SAMPANG, Indonesia telah memasuki usia 41 tahun pasca ratifikasi Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (CEDAW) sejak tahun 1984. Langkah ini menandai komitmen Indonesia untuk memperjuangkan kesetaraan gender dan hak asasi perempuan di tanah air.
Perjalanan panjang ini tidak hanya membutuhkan pengesahan regulasi, tetapi juga implementasi yang solid di dalam kehidupan sehari-hari. Apa sebenarnya dampak dari pengesahan ini bagi perempuan di Indonesia? Mari kita simak lebih dalam.
Pentingnya Regulasi untuk Memperjuangkan Kesetaraan Gender
Pemerintah Indonesia telah melakukan berbagai upaya untuk memastikan penerapan CEDAW melalui sejumlah regulasi penting. Dimulai dengan pembentukan Kementerian Urusan Wanita di era Orde Baru dan disusul oleh pendirian Komnas Perempuan di awal reformasi. Beberapa undang-undang seperti UU Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), UU Tindak Pidana Pemberantasan Perdagangan Orang (UU TPPO), serta afirmasi kuota 30% dalam UU Pemilu menunjukkan langkah progresif yang diambil.
Satu pencapaian terbaru adalah disahkannya UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang menjadi tonggak penting dalam perlindungan perempuan dari kekerasan. Menurut Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, regulasi ini menjadi catatan penting dalam perbaikan situasi di ranah kebijakan hukum setelah ratifikasi. Namun, tantangan nyata tetap ada, yaitu bagaimana mengawal dan memastikan bahwa penegakan hukum membawa perubahan budaya yang diharapkan.
Tantangan dalam Implementasi dan Budaya Baru Anti Diskriminasi
Pengesahan UU tidak boleh menjadi garis akhir dari perjuangan untuk kesetaraan gender. Implementasi dan pengawasan terhadap hukum yang ada memerlukan perhatian dan kerja keras dari semua pihak. Willy menekankan bahwa budaya baru anti diskriminasi harus terbentuk setelah adanya regulasi, dan ini menjadi tanggung jawab kolektif masyarakat.
Politik penyusunan anggaran yang mendukung implementasi anti diskriminasi juga menjadi isu penting. Willy mencatat kurangnya keterlibatan perempuan dalam Badan Anggaran DPR. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana kita bisa berharap pada anggaran yang adil jika representasi perempuan dalam pengambilan keputusan masih minim?
Keterlibatan aktivis perempuan dan semua lapisan yang peduli terhadap implementasi anti diskriminasi sangat dibutuhkan. Mereka harus berkolaborasi untuk membangun blok politik yang strategis, bukan hanya mengandalkan politisi perempuan, tetapi juga membuka ruang bagi semua yang peduli terhadap isu kesetaraan. Ada kemungkinan untuk menciptakan koalisi lebih besar yang dapat membuat perubahan signifikan.
Ketika berbicara tentang politik harapan, kami ingin lebih dari sekedar legislasi dan anggaran. Ini adalah kolaborasi besar untuk masa depan yang lebih baik, di mana setiap individu, tanpa memandang gender, dapat terlibat dalam perjuangan untuk kesetaraan dan hak asasi manusia. Komitmen ini harus dijalankan dengan semangat kolaboratif, seperti yang telah dilakukan saat pembuatan UU TPKS.
Dengan mengajak semua pihak untuk berpartisipasi, diharapkan perjuangan untuk kesetaraan gender dapat berjalan lebih efektif dan menyentuh lebih banyak orang. Komisi XIII siap bekerja sama dengan kementerian terkait untuk mendiskusikan peraturan yang dirasa belum cukup akomodatif. Kesepakatan bersama ini bisa menjadi langkah awal untuk memperbaiki undang-undang yang ada demi kebaikan bersama.